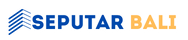Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menegaskan konsep desa wisata tidak boleh disalahartikan sebagai ajang mengubah lahan produktif—termasuk sawah—menjadi bangunan akomodasi seperti vila. Menurutnya, keberhasilan desa wisata bukan diukur semata dari seberapa ramai kunjungan wisatawan, melainkan dari seberapa kuat desa tersebut membangun kemandirian ekonomi, menjaga budaya, dan menerapkan tata kelola berbasis komunitas. Penegasan ini disampaikan sebagai pengingat bahwa desa wisata lahir dari semangat pemberdayaan masyarakat, bukan ekspansi pembangunan yang berpotensi menggerus ruang hidup warga dan fungsi ekologis pedesaan. Wamenpar menilai, desa wisata yang sehat adalah desa yang mampu memaksimalkan potensi lokal tanpa mengorbankan identitas dan lanskapnya. Ketika sawah dan ruang produksi pangan berubah menjadi deretan vila, desa kehilangan akar utamanya—yakni kehidupan agraris, sistem sosial, dan budaya yang justru menjadi daya tarik utama wisata berbasis desa.
Ni Luh Puspa menekankan bahwa desa wisata harus dipahami sebagai ekosistem, bukan sekadar destinasi. Ia menyebut ukuran keberhasilan terletak pada seberapa besar manfaat ekonomi yang kembali ke warga, seberapa kuat pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta seberapa konsisten desa menjaga tradisi, adat, dan nilai-nilai lokal. Ia menyoroti bahwa kunjungan yang tinggi tanpa tata kelola yang baik justru dapat menimbulkan masalah baru, seperti kemacetan, sampah, kenaikan harga tanah, hingga perubahan sosial yang menggeser warga lokal dari ruang hidupnya. Karena itu, Wamenpar mendorong pengelolaan desa wisata yang lebih fokus pada kualitas pengalaman wisata, distribusi manfaat yang adil, serta kontrol komunitas terhadap arah pengembangan. Dalam konteks ini, desa wisata tidak harus mengejar target massal, tetapi memastikan setiap aktivitas wisata memberi nilai tambah bagi warga, termasuk membuka lapangan kerja lokal, memperkuat UMKM, dan mendorong regenerasi pelaku budaya.
Lebih jauh, Wamenpar menyampaikan bahwa desa wisata yang ideal adalah desa yang “hidup”, artinya aktivitas wisata menyatu dengan keseharian masyarakat, bukan dibuat-buat atau dipaksakan untuk memenuhi selera pasar. Desa wisata juga harus berkelanjutan, yakni menjaga keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan budaya. Keberlanjutan, menurutnya, menuntut desa memiliki aturan yang jelas mengenai zonasi, pemanfaatan lahan, kapasitas kunjungan, serta mekanisme pengelolaan dampak seperti sampah dan penggunaan air. Ni Luh Puspa juga menekankan aspek “memanusiakan masyarakat”, yakni pembangunan pariwisata yang menempatkan warga sebagai subjek utama, bukan sekadar tenaga kerja atau objek tontonan. Desa wisata harus memberi ruang bagi warga untuk berkembang, meningkatkan pendapatan, dan tetap memiliki kontrol atas tanah, budaya, serta masa depan desanya.
Dalam penguatan desa wisata, Wamenpar mendorong desa untuk mengembangkan produk wisata berbasis potensi lokal seperti pertanian, kerajinan, kuliner tradisional, seni pertunjukan, hingga pengalaman budaya yang autentik. Pendekatan ini dinilai lebih selaras dengan konsep pariwisata berkualitas, karena wisatawan tidak hanya “datang dan foto”, tetapi terlibat dalam aktivitas yang memberi manfaat langsung bagi warga. Ia juga mengingatkan pentingnya tata kelola kelembagaan, termasuk peran pokdarwis, desa adat, dan BUMDes, agar pengelolaan tidak dikuasai segelintir pihak. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan sektor swasta juga diperlukan, namun tetap harus menjaga prinsip utama: keputusan pengembangan berada di tangan komunitas desa.
Penegasan Wamenpar ini sekaligus menjadi kritik terhadap praktik-praktik yang menyimpang dari semangat desa wisata, seperti pembangunan akomodasi berlebihan yang mengubah struktur desa dan memicu alih fungsi lahan. Ni Luh Puspa berharap seluruh pihak memahami bahwa desa wisata bukan proyek instan untuk mengejar keramaian, melainkan proses membangun kemandirian dan martabat desa. Dengan pengelolaan yang tepat, desa wisata dapat menjadi jalan bagi pemerataan ekonomi, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan. “Desa wisata harus hidup, berkelanjutan, dan memanusiakan masyarakatnya,” tegasnya, menutup pesannya bahwa inti pariwisata desa adalah kesejahteraan warga—bukan sekadar jumlah kunjungan.